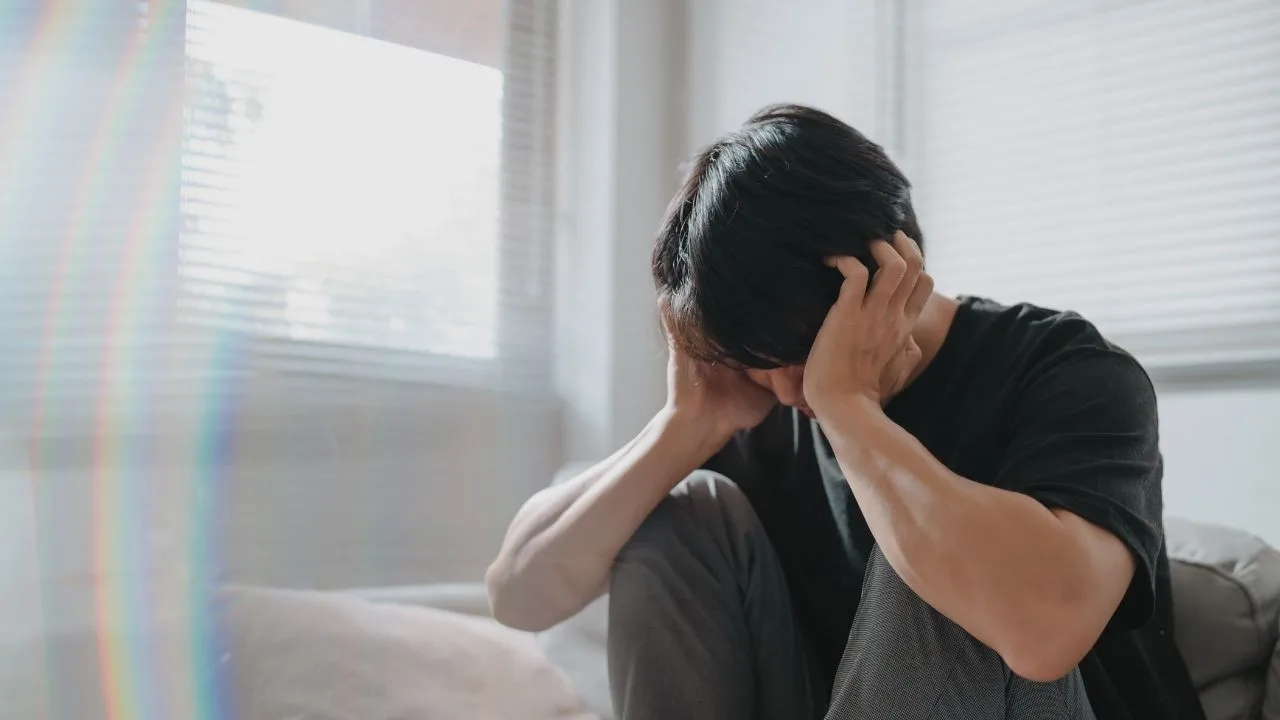TGX– Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan ada karena diciptakan oleh masyarakat, begitu pula sebaliknya tanpa kebudayaan masyarakat tidak akan ada (Fajrie, 2016). Kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat tidak terlepas dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat (Mendri & Prayogi, 2016). Terkait hal ini, kebudayaan memiliki arti atau tujuan dalam setiap bentuknya. Indonesia memiliki beranekaragam budaya, mengingat Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang multikultural, keanekaragaman ini adalah bentuk kekayaan dan keunikan yang mempunyai nilai luhur (Koentjaraningrat, 1996 :72). Indonesia memiliki keragaman budaya yang banyak, dimana hampir setiap daerah memiliki kebudayaan yang berkembang di daerahnya masing-masing tergantung dari kondisi daerah tersebut. Salah satu daerah yang memiliki keragaman budaya adalah Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Daerah ini dikenal memiliki tradisi multikultural yang tumbuh subur, salah satunya adalah Reog Bulkiyo.
Reog Bulkiyo adalah tari tradisional yang diciptakan oleh pasukan pangeran Diponegoro yang melakukan persembunyian di desa Kemloko kabupaten Blitar pada tahun 1825. De Javasche Oorlog merupakan peristiwa perang di tanah Jawa yang berlangsung antara tahun 1825-1830 yang lebih dikenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Menurut Ma’arif (2014: 93-94) Perang Jawa adalah perang antara Pangeran Diponegoro bersama rakyat Jawa melawan Belanda karena sikap sewenang-wenangnya terhadap Kesultanan Yogyakarta. Menurut Carey (2011:704) penyebab utama Perang Diponegoro adalah ketika pemerintah kolonial memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogya, satu di antaranya melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Struktur organisasi perang Pangeran Diponegoro berbentuk corps, yang meniru organisasi tentara kerajaan Turki Ustmani pada abad ke 16-18. Pasukan elit kerajaan Turki Utsmani terdiri atas tiga divisi yaitu Boluck, Cemaat, dan Segmen. Pasukan infantrinya disebut Bashiboluck, nama-nama Turki tersebut diadopsi oleh Pangeran Diponegoro dengan lafal Jawa.
Boluck menjadi Bulkiyo, Bashiboluck menjadi Borjomuah, Turki menjadi Turkiyo demikian pula pangkat komandan dan prajurit. Pangkat untuk pemimpin tertinggi adalah Ali Basah, hanya beberapa orang saja yang berpangkat Ali Basah, antara Ali Basah Sentot Prawiridirjo, Ali Basah Kerto Pengalasan dan Ali Basah Mohamad Ngusman (Leirissa, 2009: 233). Pada tanggal 25 Maret 1830 Jendral De Kock dengan secara rahasia memberi instruksi untuk menangkap Pangeran Diponegoro apabila perundingan gagal. Penundaan selama kira-kira 2 hari dalam bulan Ramadhan, memberi kesempatan pada Belanda untuk kemudian merencanakan penangkapannya. Perundingan yang diadakan pada tanggal 28 Maret 1830 ternyata berakhir dengan kegagalan dan Pangeran Diponegoro ditangkap (Leirissa,1990: 204). Tertangkapnya Pangeran Diponegoro mengakibatkan perlawanan selama 1825-1830 tidak membuahkan hasil, banyak pengikut Pangeran Diponegoro yang menyerahkan diri terhadap Belanda dan sisa sisa prajurit banyak yang melarikan diri di berbagai daerah pelosok agar tidak tertangkap oleh pasukan Belanda, karena setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, Belanda akan mencari dan menangkap sisa-sisa prajurit Pangeran Diponegoro yang dimungkinkan melakukan pemberontakan lagi.
Blitar adalah salah satu tempat pelarian sisa-sisa Pangeran Diponegoro, sebab daerah Blitar secara geografis merupakan tempat di mana keadaan tanah sangat subur, mengingat bahwa masih berada dekat dengan gunung Kelud yang masih aktif. Selain keadaan tanah subur yang bisa dijadikan sisa-sisa prajurit Pangeran Diponegoro untuk bertahan hidup dengan cara membuka lahan untuk bertani, tempat ini masih banyak hutan dan pemerintah Belanda belum menaruh perhatian khusus pada Blitar sebelum terbentuknya Gementese-hingga aman untuk persembunyian atau penyamaran sisa-sisa prajurit oleh pencarian pasukan Belanda. Bermula dari peristiwa inilah suatu kesenian tari tradisional Reog Bulkiyo di Desa Kemloko Kecamatan Ngglegok, Kabupaten Blitar tercipta oleh Kasan Muhtar dan masih lestari hingga saat ini. Kasan Muhtar merupakan salah satu prajurit Pangeran Diponegoro berasal dari Bagelan, Jawa Tengah yang melarikan diri di daerah pelosok Blitar. Nama Reog Bulkiyo kemungkinan besar diambil dari salah satu corps prajurit Pangeran Diponegoro yaitu corps Bulkiyo, mengingat bahwa yang menciptakan kesenian tersebut merupakan salah satu sisa-sisa parajurit yang melarikan diri serta gerak tarinya serupa gerakan olah kanuragan prajurit yang berperang menggunakan pedang.
Gerakan dalam seni Reog Bulkiyo dimodelkan sebagai tarian prajurit dalam gerakan perang melawan penjajah, sehingga keterampilan perang prajurit di dalam tarian ini digambarkan dengan senjata tajam. Karena, memang pada awalnya tarian ini adalah gerakan sabung (latihan perang), sarana dakwah dan juga silaturahmi masyarakat islam yang dilakukan oleh prajurit Bulkiyo(pasukan pemanah pangeran Diponegoro). Dari peralatan musik yang mengiringi mengandung tiga unsur budaya yaitu Jawa, Arab, dan Cina. Kembali pada Reog Bulkiyo, suatu karya seni sebagai representasi Perang Jawa sangat wajar bahwasanya kesenian itu mengandung tiga unsur budaya. Budaya Jawa, mengingat peristiwa perang terjadi hampir di seluruh Jawa, budaya Islam Arab, karena sang pemimpin Perang Jawa, Pangeran Diponegoro yang merupakan penganut mahzab Islam Sufisme serta adanya motivasi Perang Jawa adalah mendirikan negara Islam (Balad). Warna budaya Cina juga memperlihatkan akulturasi pada Reog Bulkiyo, sebab ketika peristiwa Perang Jawa orang Tionghoa (Cina) yang menjadi sasaran operasi perang, meskipun dalam perkembangannya, menurut Djamhari (2014: 105) pasukan Pangeran Diponegoro juga membeli senjata dari Orang Cina.
Dari segi perlengkapan dan peralatan juga terdapat akulturasi dari tiga budaya. Pertama, budaya Jawa diantaranya Blangkon dengan gaya Yogyakarta, kain batik bermotif parang rusak, baju Beskap dan Atela. Blangkon yang dipakai para penari ada dua macam yaitu, Blangkon dengan mondholan dan Blangkon dengan gayasintingan keduanya khas gaya Yogyakarta. Ada yang dari Blangkon yang dipakai penari pembawa alat musik terbang (Penari Prajurit), sebuah perpaduan blangkon dengan lilitan kain merah dan putih disebut Udeng Gilik Bawang Sebungkul. Atribut ini hampir mirip dengan pakaian perang pasukan Janisari Turki Ustmani abad 16. Keris, dipakai oleh setiap penari Reog Bulkiyo Blitar. Keris yang dipakai bergaya Yogyakarta dengan warngka branggah. Cara yang digunakan untuk memakai keris juga bergaya mogleng Yogyakarta. Dengan demikian, jika kita tarik benang merah, antara sejarah singkat, ciri khas, dan motif atau gaya busana Reog Bulkiyo, adalah seni tari identitas para pelaku seninya. Identitas untuk para pejuang ketika Perang Jawa terjadi, di sisi lain, dimungkinkan juga sebuah seni identitas ini untuk memberitahukan kepada sanak saudara yang nasibnya sama-sama sebagai pelarian masa Perang Jawa berakhir tahun 1830. (*/khr)
Penulis: Gerwin Satria Nirbaya
Editor: Akhmad Nur Khoiri
Daftar Rujukan
Carey, Peter B.R. (2011). Kuasa Ramalan (Jilid II). Pangeran Diponegoro dan Akhir tatanan lama di Jawa 1785 – 1855. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
Djamhari, Saleh As’ad. (2014). Strategi Menjinakan Diponegoro (Stelsel Bneteng 1827 – 1830). Jakarta: Komunitas Bambu.
Fajrie, M. (2016). Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah: Melihat Gaya Komunikasi dan Tradisi Pesisiran. Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi.
Leirissa, R.Z. (1990). Sejarah Nasional Indonesia (jilid IV). Jakarta: Balai Pustaka.
Leirissa, R.Z. (2009). Sejarah Nasional Indonesia IV (edisi Pemutakhiran). Jakarta: Balai Pustaka.
Ma’arif, Syamsul. (2014). Jejak Kesaktian Dan Spiritual Pangeran Diponegoro. Yogyakarta: Araska